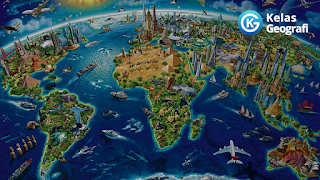Apa Itu Interaksi Desa dan Kota: Pengertain, Faktor Pendorong, dan Dampaknya
Kelas 12Desa menyediakan kebutuhan dasar berupa hasil pertanian yang diperlukan oleh masyarakat kota, sementara kota menyuplai kebutuhan pokok berupa barang jadi hasil industri yang dibutuhkan oleh penduduk desa. Hubungan timbal balik antara desa dan kota ini dikenal dengan istilah interaksi desa-kota.
 |
| Apa saja interaksi antara desa dan kota? Apa yang dimaksud interaksi keruangan desa dan kota? Apa itu zona interaksi desa dan kota? Faktor apa yang mempengaruhi interaksi desa dan kota? |
Dalam kaitannya dengan kota, desa memiliki peran spesifik sebagai hinterland atau daerah penyangga. Desa memainkan peran dalam penyediaan bahan makanan pokok, baik dari sektor pertanian tanaman maupun peternakan. Selain itu, desa juga berfungsi sebagai sumber bahan mentah dan tenaga kerja produktif yang dibutuhkan oleh kawasan perkotaan. Berbagai komoditas primer seperti beras, jagung, sayuran, dan buah-buahan dihasilkan dari wilayah pedesaan.
Faktor Pendorong Interaksi Desa-Kota
1. Komplementasi Regional (Regional Complementary)
Komplementasi regional berarti keterkaitan antardaerah yang saling melengkapi. Interaksi antarwilayah terjadi apabila suatu wilayah memiliki potensi yang dapat memenuhi kekurangan wilayah lain. Misalnya, kebutuhan kota Malang akan beras dan sayuran dapat dipenuhi oleh desa-desa di Pakis yang letaknya berdekatan.
2. Kesempatan Intervensi (Intervening Opportunity)
Kesempatan intervensi merujuk pada faktor yang berpotensi menghambat terjadinya interaksi antarwilayah. Hal ini terjadi ketika terdapat sumber daya alternatif yang dapat menggantikan sumber daya utama. Sebagai contoh, kelangkaan sayur dapat diatasi melalui praktik pertanian di wilayah kota atau urban farming.
3. Kemudahan Perpindahan dalam Ruang (Spasial Transfer Ability)
Kemudahan mobilitas atau perpindahan dalam ruang menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya interaksi antarwilayah. Perpindahan manusia, barang, dan informasi sangat mempengaruhi intensitas interaksi. Faktor ini berkaitan erat dengan jarak fisik maupun jarak ekonomis antarwilayah, ongkos transportasi, serta keberadaan infrastruktur dan kelancaran sarana transportasi. Contohnya, hasil pertanian dari desa-desa di sekitar Malang dapat dikirimkan dengan mudah karena akses jalan dan transportasi yang mendukung (Suparmin, 2012).
Dampak Positif Interaksi Desa-Kota
1. Peningkatan Pengetahuan dan Literasi Masyarakat
Kemudahan dalam mengakses dan bertukar informasi mendorong peningkatan pengetahuan dan literasi masyarakat. Seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, terutama sejak memasuki era milenial, internet telah memberikan kontribusi besar bagi masyarakat dalam hal penambahan wawasan dan akses terhadap berbagai informasi penting (Talika, 2016).
2. Peningkatan Pergerakan Barang dan Jasa
Adanya pertumbuhan aktivitas pengiriman barang dan penyediaan jasa baik dari desa ke kota maupun sebaliknya. Kota sebagai pusat ekonomi modern menawarkan sumber penghasilan yang lebih beragam, terutama di bidang jasa yang berkembang lebih cepat dibandingkan produksi barang. Untuk memenuhi kebutuhan pokok yang tidak tersedia di kota, maka produk dari desa pun menjadi pilihan.
3. Penciptaan Akses Teknologi yang Lebih Mudah
Masyarakat desa kini lebih mudah dalam mengakses teknologi tepat guna, khususnya di sektor pertanian. Pemerintah mendorong petani dan generasi muda desa untuk memanfaatkan teknologi pertanian melalui pelatihan dan penyuluhan, serta pemberian alat-alat pertanian modern. Tujuannya agar teknologi tersebut dapat diterapkan secara langsung di lahan pertanian desa.
Dampak Negatif Interaksi Desa-Kota
1. Peningkatan Urbanisasi
Akses transportasi yang semakin terbuka antara desa dan kota membuat masyarakat usia produktif lebih memilih bekerja di kota. Motif ekonomi menjadi pendorong utama perpindahan penduduk desa ke kota. Kota memberikan berbagai peluang seperti lapangan kerja yang luas, gaji yang lebih tinggi, serta sarana dan prasarana yang memadai, sehingga menarik minat masyarakat untuk bermigrasi.
2. Penurunan Lahan Pertanian dan Ruang Terbuka Hijau
Pertumbuhan jumlah penduduk berdampak pada berkurangnya ruang terbuka hijau dan lahan pertanian. Semakin banyak penduduk berarti semakin besar pula kebutuhan akan lahan pemukiman atau usaha, sementara ketersediaan lahan tidak bertambah. Akibatnya, lahan-lahan produktif dialihfungsikan untuk kegiatan permukiman atau ekonomi lainnya.
3. Penetrasi Budaya Kota yang Tidak Selaras dengan Budaya Desa
Penetrasi budaya mengacu pada masuknya unsur budaya baru ke dalam budaya lokal yang telah lama dikenal (Putri, 2021). Pengaruh budaya kota bisa jadi tidak sejalan dengan budaya desa. Meski tidak selalu negatif, jika budaya lama dan baru tidak dapat berjalan berdampingan, maka budaya lokal bisa saja tergerus.
4. Timbulnya Permasalahan Sosial
Munculnya masalah sosial seperti pengangguran, tunawisma, dan kriminalitas menjadi konsekuensi dari urbanisasi yang tidak dibarengi dengan kesiapan keterampilan kerja masyarakat desa. Ketidaksiapan ini menyebabkan banyak pendatang desa kesulitan mendapatkan pekerjaan, yang pada akhirnya meningkatkan angka pengangguran dan kemiskinan, serta memicu tindakan kriminal (Harahap, 2013).
5. Munculnya Kawasan Kumuh (Slum Area)
Pertumbuhan penduduk akibat urbanisasi mempercepat terbentuknya kawasan permukiman kumuh di tengah kota. Ciri khas kawasan ini adalah lingkungan yang padat, tidak tertata, dan tidak layak huni. Banyak warga kota yang tinggal dalam kondisi sempit di daerah-daerah seperti bantaran sungai, kolong jembatan, tepi rel, dan kawasan perdagangan. Kawasan kumuh terus berkembang dengan penambahan penghuni yang meningkat dua kali lipat setiap lima hingga sepuluh tahun.
6. Menurunnya Minat Terhadap Sektor Pertanian
Pekerjaan di luar sektor pertanian semakin menarik karena dianggap lebih menjanjikan dari sisi penghasilan. Imbasnya, generasi muda semakin enggan bekerja di bidang pertanian. Padahal Indonesia merupakan negara agraris. Jumlah tenaga kerja di sektor pertanian pun menurun dari 42,46 juta orang pada tahun 2011 menjadi 38,77 juta orang pada tahun 2021.
7. Meningkatnya Gaya Hidup Hedonisme
Gaya hidup hedonis mulai marak di masyarakat desa, terlihat dari tingginya konsumsi terhadap barang-barang industri. Fenomena ini dipicu oleh banyaknya produk yang beredar di pasar dan memicu masyarakat untuk membeli tidak lagi berdasarkan kebutuhan, melainkan keinginan seperti mengikuti tren, gengsi, atau untuk meningkatkan status sosial (Anggraini & Santhoso, 2020).